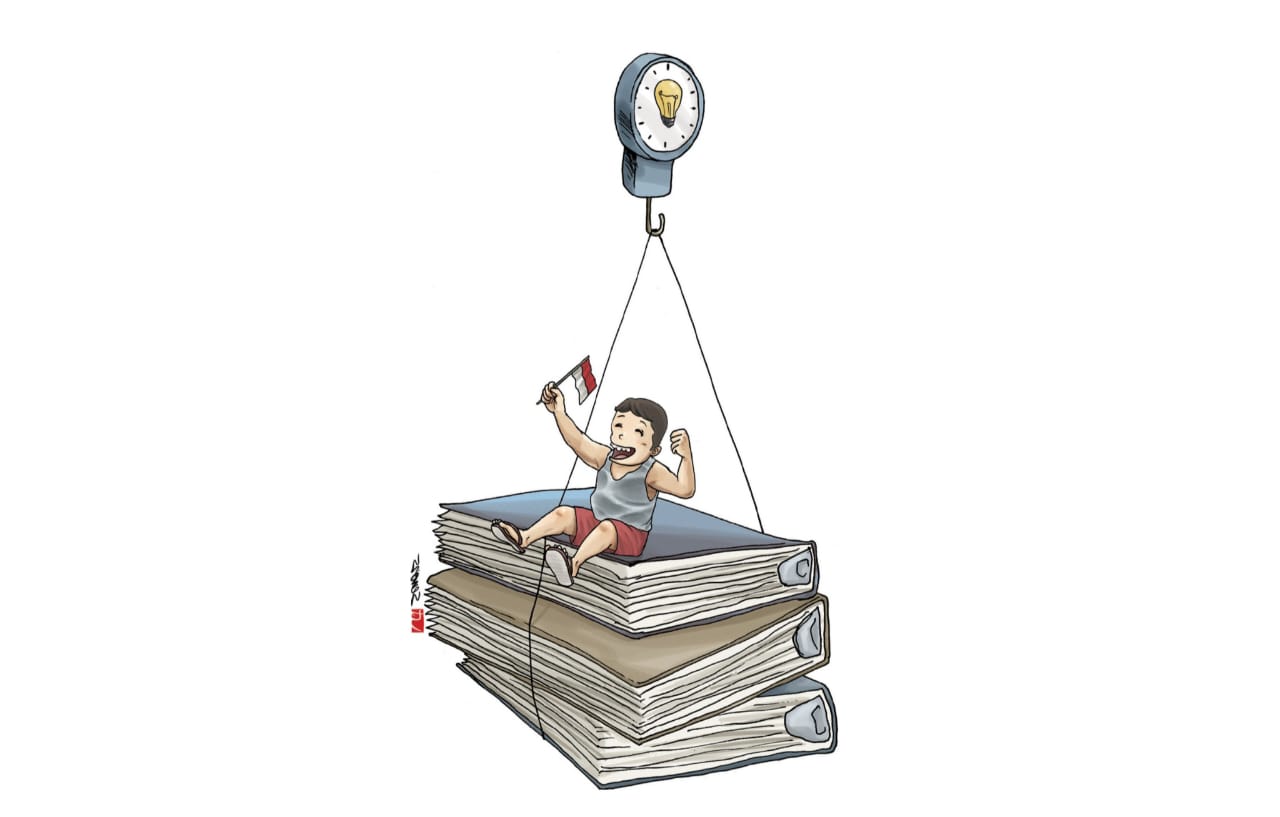 (MI/Seno)
(MI/Seno)
SALAH satu misi fundamental didirikannya negara ini ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa itu mencerdaskan kehidupan bangsa? Ialah mencerdaskan akal budi warga negara Republik Indonesia agar dalam kapasitasnya sebagai bangsa, ia mampu menunjukkan diri, mampu berperan aktif, dan mampu menjadi relevan dalam interaksi dan dialektika kehidupan warga dunia.
Agar hal itu terwujud maka proyek pembangunan nasional mestilah beraras pada penguatan akal budi anak bangsa. Terkait dengan hal ini, kita tidak bisa menafikan peran penting dari keberadaan buku. Buku bukan sekadar bacaan atau media untuk dibaca. Buku juga bukan sekadar kumpulan kertas yang disusun hingga berhalaman banyaknya. Buku adalah wahana di mana pemikiran dituangkan, di mana gagasan diabadikan serta di mana rasa ditumpahkan. Buku adalah storage pemikiran dan gagasan bagi penulis sekaligus wahana di mana pembaca bisa mengaksesnya.
Buku adalah ruang di mana kegiatan membaca dan menulis berdialektika. Buku adalah manifestasi kebudayaan tertinggi manusia karena di sanalah aksara dan tanda berkumpul membangun gagasan. Buku laksana jembatan di antara makhluk pemikir bernama manusia berdiskursus.
MENCERAHKAN AKAL BUDI MANUSIA
Kita sering lupa, Indonesia merdeka bukanlah hadiah. Ia diperjuangkan oleh berbagai pemikiran besar yang lahir dari rahim literasi berupa buku. Ia lahir dari spirit zaman yang haus akan pengetahuan. Terkait hal tersebut, kita punya sejarah emas berupa Balai Pustaka yang pada masanya menjadi pusat peradaban; yang tidak pernah mengategorikan dan memisah-misahkan antara buku umum dan buku sekolah. Karena, bagi para pendiri bangsa, pengetahuan adalah satu kesatuan utuh untuk mencerahkan akal budi manusia.
Kita harus menghadapi sebuah realitas yang getir di mana data menunjukkan bahwa skor Programme for International Student Assessment (PISA) kita secara konsisten menempatkan kita di papan bawah dunia. PISA adalah angka yang menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam bidang literasi membaca, matematika, dan sains. Ini bukan sekadar angka statistik yang bisa kita abaikan atau maklumi begitu saja. Ini adalah alarm darurat bagi masa depan bangsa. Ini pertanda kita sedang berisiko melahirkan generasi yang tidak siap bersaing dan sekadar menjadi generasi konsumen.
Di sisi lain, kita bisa melihat paradoks digital kita. Indeks literasi digital menunjukkan bahwa kita sangat cakap menggunakan gawai, tetapi pada saat yang sama kita menjadi salah satu konsumen hoaks terbesar di dunia. Saya sering melihat, dan ini menyedihkan, orang-orang terpelajar, bahkan profesor sekalipun, banyak yang termakan hoaks. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita hanya bisa membaca, tapi tidak terlatih untuk berpikir kritis.
Literasi kita berhenti pada kemampuan mengeja kalimat, belum sampai pada kemampuan mencerna, menimbang, dan mendialektikakan gagasan. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa berada dalam kultur berdialog, berdiskursus, hingga berdialektika yang kuat.
Realitas lain menyampaikan pada kita tentang toko-toko buku, yang dulu menjadi surga pengetahuan, sekarang tutup satu per satu. Orang sudah tidak mau lagi membaca. Di Jogja, kota yang dulu dikenal sebagai surganya buku, denyutnya sudah tidak seperti dulu. Dulu ada Gamapres, tempat pertama yang saya kunjungi saat masuk Jogja. Sekarang tempat itu sudah tutup. Social agency seperti Togamas, satu per satu meredup atau bahkan lenyap. Ini adalah alarm bagi kematian infrastruktur pengetahuan kita secara perlahan.
Yang paling membuat hati lebih miris lagi ialah ketika saya pulang ke Sumatra Barat. Di Pasar Ateh, Kota Padang, kota yang banyak melahirkan peradaban adiluhung, yang melahirkan Buya HAMKA dan begitu banyak pemikir besar bangsa, saya melihat dengan mata kepala sendiri buku-buku dijajarkan dengan kandang hewan dan salon plus-plus.
Can you can imagine it?! Begitu ternyata cara kita menempatkan keberadaan buku hari ini?! Di masanya, Buya HAMKA adalah seorang penulis produktif, dan di zamannya telah berdiri delapan penerbit buku: sebuah indikator yang menunjukkan betapa semaraknya dunia perbukuan kala itu.
Belum lagi jika kita mengingat Hatta, Yamin, Syahrir, Tan Malaka, dll, betapa mengharu pilu kita melihat kenyataan di atas. Semua ini menjadi kenyataan yang banal sekaligus cermin paling telanjang tentang bagaimana begitu abai dan rendahnya kita menempatkan pengetahuan dalam kehidupan kita sebagai makhluk berakal.
Semua kenyataan itu seolah terkonfirmasi dengan data yang mestinya membuat kita tidak bisa tidur nyenyak: IQ rata-rata bangsa kita telah turun secara gradual. Di zaman Pak Harto, angkanya ada di kisaran 83, 82. Hari ini, angkanya berada di kisaran 78. Turun! Dan ini adalah sinyal dari kemunduran sebuah peradaban.
Di sisi lain, buku telah menjadi barang mewah bagi kita. Di negara seperti Jerman, seorang pekerja hanya butuh menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk membeli buku. Di sini? Seorang pekerja di Jakarta harus merelakan porsi upah minimumnya yang cukup besar untuk memiliki sebuah buku.
Dari India, saya pernah membawa pulang tiga koper besar buku. Mengapa bisa demikian? Karena harga buku di sana luar biasa murah! Ada yang cuma lima ribu rupiah, sepuluh ribu rupiah; dengan kualitas buku seharga ratusan ribu rupiah di sini.
Dari mana semua kekacauan ini bermula? Salah satu akar masalahnya, dalam hemat saya pribadi, ialah cara pandang kita yang terjebak dalam penyempitan antara buku sekolah dan buku umum. Undang-undang yang saat ini ada, terlalu berat pada intervensi buku teks. Saya paham alasan bahwa ini merupakan upaya sinkronisasi antara UU Sisdiknas dan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Niatnya mungkin baik, tapi dampaknya ternyata cukup fatal. Apa yang disebut buku umum dianggap sebagai urusan privat, urusan bisnis, untuk kemudian diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar kita yang rapuh. Akibatnya pengetahuan menjadi terasa begitu mahal dan tak berakses.
Bagi saya pribadi, ini adalah sebuah kekeliruan fundamental. Mengapa yang namanya pengetahuan mesti dipisah-pisah? Seolah-olah pengetahuan di luar sekolah itu tidak penting. Seolah-olah membangun imajinasi lewat novel, membuka wawasan lewat buku filsafat, atau belajar skill baru dari buku nonfiksi itu bukan bagian dari ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Tembok pemisah inilah yang telah memenjarakan potensi intelektual bangsa kita selama ini.
EMPAT PILAR
Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kenyataan ini? Jawabannya bukan membuat regulasi yang lebih ketat. Jawabannya juga bukan kontrol yang lebih rumit. Jawabannya ialah membangun sebuah ekosistem yang hidup, yang berdenyut, yang kolaboratif, dan yang memiliki spirit membebaskan atas kehidupan buku di Tanah Air.
Setidaknya ada empat pilar untuk kita memulainya. Pilar pertama ialah soal konten dan akses global. Kita harus punya proyek peradaban yang berani. Kita harus menghidupkan kembali Balai Pustaka, bukan sebagai museum yang kita kenang, tapi kita restorasi fungsinya menjadi pusat penerjemahan dan literasi modern yang relevan. Kita bisa belajar dari India yang mampu mengundang penerbit dunia untuk mencetak edisi murah dengan kualitas kertas terjangkau agar rakyat bisa membeli.
Pilar kedua ialah kolaborasi dan keterlibatan publik. Negara tidak bisa, dan tidak boleh, bekerja sendirian. Kita harus mengundang semua kekuatan bangsa; ya pemikirnya, ya penggerak literasinya, ya penerbitnya, ya para influencer, ya para pengusahanya; untuk bersama-sama merumuskan bangunan ekosistem yang suportif terhadap kerja peradaban ini. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Ini strategi agar semua merasa menjadi bagian dari gerakan ini, part of the movement.Pilar ketiga ialah kebijakan yang membebaskan. RUU Perbukuan yang tengah berproses ini berprinsip open source dan antimonopoli. Biarkan gagasan lahir dari mana saja. Jangan lagi negara sibuk untuk mengatur hal-hal sifatnya privat seperti royalti. Biarkan itu menjadi urusan bisnis di mana negara hanya memfasilitasi agar keadilan bisa dirasakan oleh segenap stakeholder
. Fokus negara ialah sebagai fasilitator. Prinsipnya harus sederhana: hidupi mereka semua yang mau menulis, mencetak, menerbitkan buku. Dan, yang terpenting, hapuskan pajak untuk semua buku! Hal semacam ini seharusnya tidak ada di negara yang amanat konstitusinya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Adapun pilar keempat ialah ruang dan gerakan. Literasi itu butuh ruang. Kita harus mendorong lahirnya ruang-ruang literasi di berbagai daerah. Konsepnya sederhana saja, tapi efektif. Saya pribadi sudah memulainya. Saya mendirikan ruang literasi di Jogja. Di sana ada perpustakaan umum, ada perpustakaan anak, ada pula aktivitas dan komunitas yang menyelenggarakan kegiatan intelektual, mulai...

 4 hours ago
2
4 hours ago
2

















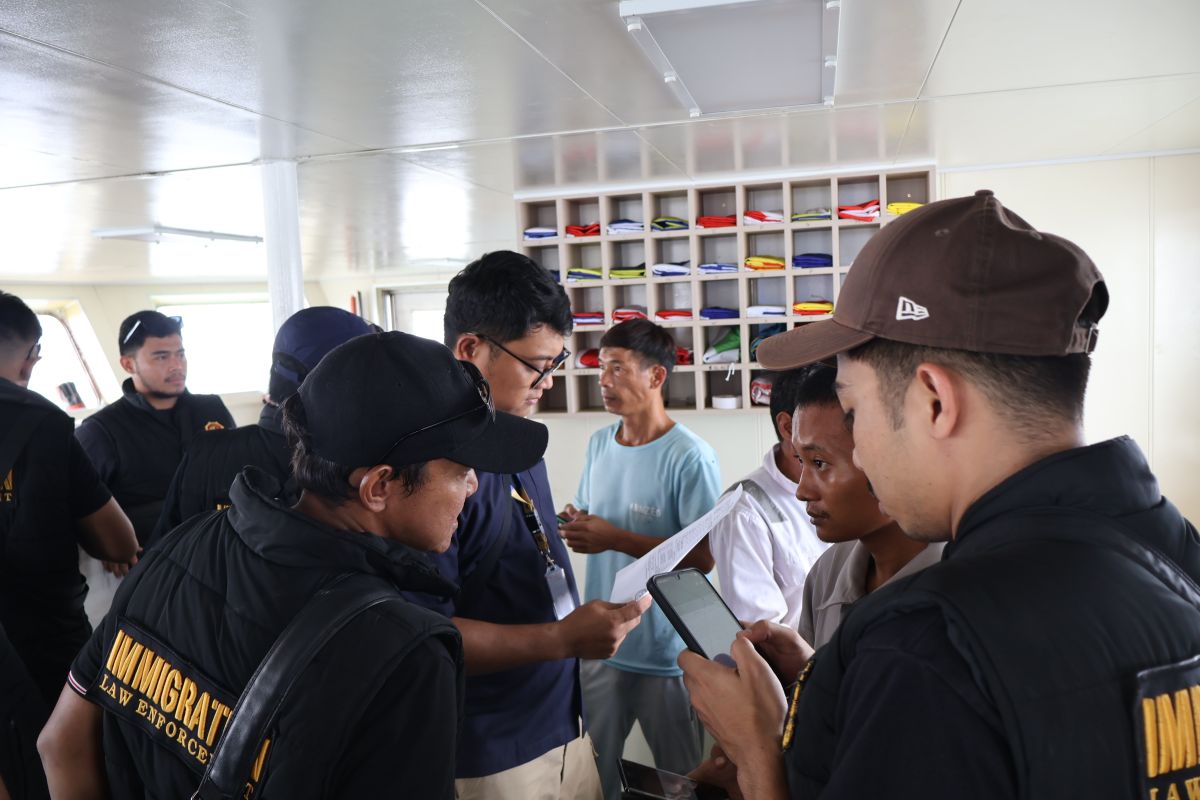




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5307706/original/034270900_1754476306-Glare_Free_Samsung.jpeg)



:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5308800/original/005524700_1754555604-Indosat_Ooredoo_Hutchison_02.jpeg)


:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,1100,20,0)/kly-media-production/medias/5278334/original/082633500_1752063732-Galaxy_Z_Fold7_dan_Flip7_02.jpg)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5310131/original/064513800_1754659554-Foto_1__9_.jpeg)





